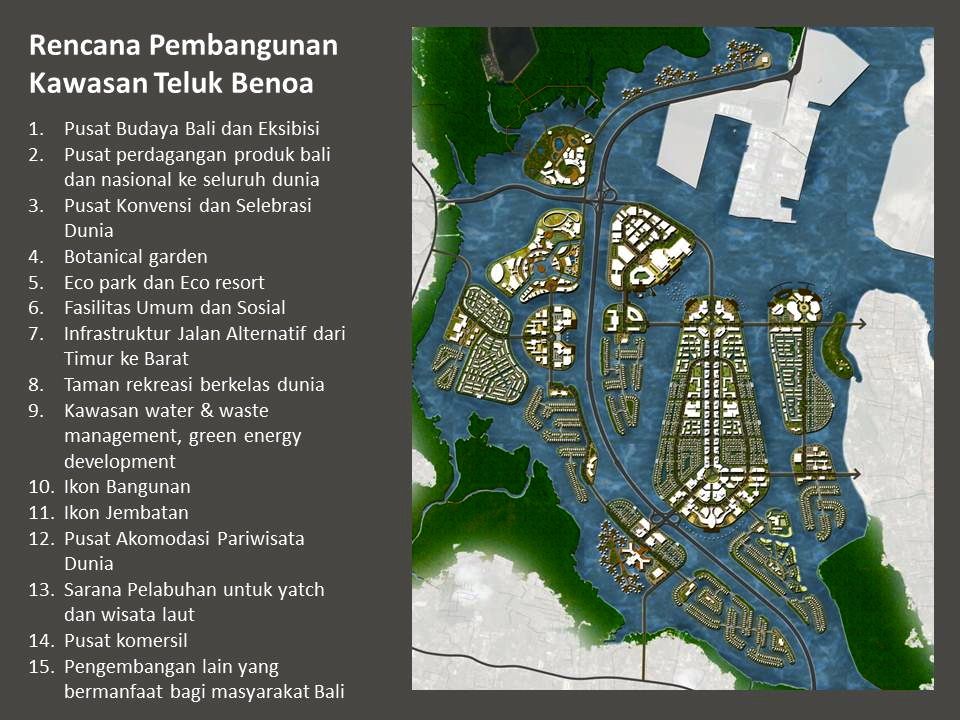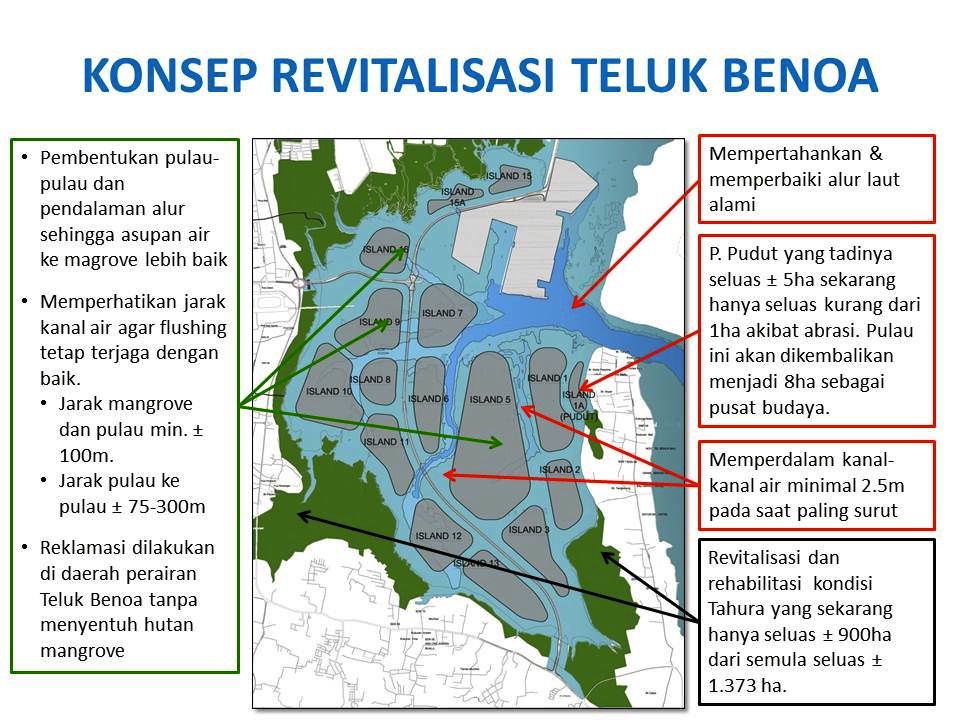![]()
Inilah aksi aparat yang mulai mendatangi ibu-ibu yang ada di tenda. Para ibu ini sudah hampir tujuh bulan hidup ditenda demi mencoba menghalang-halangi perusahaan (PT Semen Indonesia), membangun pabrik dan menambang karst. Mereka khawatir lingkungan rusak dan sumber air hilang, otomatis sumber kehidupan wargapun hilang. Foto: Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng
Di Sinjai, Sulawesi Selatan, Bahtiar Sabang, seorang petani, kini masih mendekam dalam tahanan, gara-gara menebang sebatang pohon yang ditanam dan di kebun sendiri, yang diklaim pemerintah masuk kawasan hutan. Di Banggai, Sulawesi Tengah, Eva Bande mendekam di penjara gara-gara berjuang bersama warga mempertahankan lahan pertanian mereka dari jarahan pemodal.
Sedang di Rembang, Jawa Tengah, sudah hampir tujuh bulan ini, ratusan ibu-ibu aksi dalam tenda demi protes mempertahankan lingkungan dan sumber air kehidupan mereka yang terancam jika perusahaan menambang di karst Pegunungan Kendeng.
Kasus-kasus itu hanya segelintir dari perjuangan warga mempertahankan hak-hak mereka di berbagai daerah. Hak asasi mereka untuk hidup, berusaha, bekerja dan mendapatkan lingkungan sehat belum dipenuhi negara. Bahkan kala mereka berusaha mempertahankan itu, kekerasan dari negara yang mereka peroleh, harus berhadapan dengan aparat.
Belum lagi jutaan masyarakat adat di Indonesia, yang tak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak. Sejauh ini, respon pemerintah baru sebatas kebijakan yang belum berjalan baik di lapangan. Hingga masyarakat adat di nusantara ini belum bisa hidup merdeka karena terusir dari wilayah hidup mereka sendiri. Wilayah-wilayah adat belum diakui. Kala mereka berusaha mempertahankan hak hidup, tak sedikit mendekam di penjara, luka-luka sampai tewas.
Sepuluh Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Sedunia. Bisa dibilang, Indonesia, masih mendapatkan rapor merah dalam pemenuhan HAM bagi warga di sektor sumber daya alam dan agraria. Berbagai kalangan, di berbagai daerah memperingati Hari HAM ini. Mereka menuntut dan mendesak dan mengingatkan pemerintah akan pemenuhan hak-hak dasar warga ini.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, Solidaritas Anti Kekerasan (Sontak), aksi di Flyover Makassar. Koalisi ini gabungan berbagai elemen masyarakat, antara lain Walhi Sulsel, Lembaga Bantuan Hukum (LBM) Sulsel, Kontras Sulawesi, Suara Perempuan (SP) Anging Mammiri, Sehati, Amara, Geramdan sejumlah lembaga kemahasiswaan.
Sejumlah aksi kekerasan dilakukan aparat terhadap petani di Kabupaten Takalar dan Sinjai adalah catatan buruk penegakan HAM di Sulsel. Hingga kini, belum ada sanksi kepada kepolisian yang melakukan kekerasan.
“Mekanisme sanksi kepada aparat yang melakukan kekerasan sangat minim. Biasa hanya sanksi internal terkait kode etik,” kata David dari Kontras Sulawesi.
Dia mencontohkan, konflik petani dan PTPN XIV di Takalar. Saat itu kepolisian bersama TNI melakukan kekerasan fisik kepada petani yang menghalangi pengolahan lahan bersengketa dengan PTPN.
“Ada tiga warga ditangkap yaitu Daeng Ngamin, Mangun dan Mangun. Kedua Daeng Mangun masih ditahan. Laporan warga akan ketua DPRD Takalar justru tidak diproses.”
Kasus lain penangkapan Bahtiar Sabang, petani dari Desa Turungan Baji, Sinjai, hanya karena menebang sebatang pohon di kebun sendiri, yang diklaim milik hutan produksi terbatas pemerintah. Sedang status kawasan hutan masih penunjukan, belum penetapan.
Aksi mereka di tengah guyuran hujan. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, khusus Presiden Joko Widodo, antara lain menggunakan momentum Hari HAM ini untuk mempublikasikan kerja-kerja startegis dalam penuntasan berbagai kasus HAM.
![]()
Bahtiar menanggung nasib menjadi tahanan Polres Sinjai sejak 13 oktober 2014 hanya karena tuduhan menebang pohon di kebun sendiri, di mana kawasan itu menurut pemerintah daerah masuk kawasan hutan produksi. Foto: Wahyu Chandra
Aksi ini juga meminta Kapolri, Panglima TNI dan BIN mengevaluasi berbagai tindakan kekerasan aparat, baik kepada petani, jurnalis, buruh, dan mahasiswa.
“Kami meminta mereka menghentikan penggunaan kekerasan dalam menghadapi warga, dengan membuat terobosan baru yang mendorong profesionalisme dan akuntabilitas aparat.”
Selain menggusung isu sumber daya alam dan konflik petani, aksi ini juga menyoroti kasus penembakan masyarakat adat di Papua, kekerasan jurnalis dan mahasiswa kala aksi penolakan harga BBM naik. Pembebasan bersyarat buat Polycarpus, tak luput dari sorotan.
“Stop temba’-temba’ Pak Polisi,” teriak Amin, aktivis Walhi.
Sedangkan aktivis Suara Perempuan menyuarakan keadilan bagi perempuan dan tuntutan penghapusan kebijakan tidak pro gender.
Aksi unjuk berjalan cukup unik, karena polisi yang berjaga jauh melebihi pengunjuk rasa. Belasan Polwan sempat berbaur dengan pengunjuk rasa dan mengajak bercanda. Pemandangan lain, keterlibatan Brimob dalam mengatur lalu lintas dan Provos mengawasi aksi.
Terpisah, Asmar Exwar, Direktur Walhi Sulsel, menyatakan, peringatan ini seharusnya menjadi momentum pemerintah memajukan isu-isu HAM. Upaya pemerintah mengundang investasi, seharusnya dibarengi kajian benar tentang dampak kepada lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Ketika investasi masuk, berpotensi konflik ruang antarpemerintah dan investor dengan masyarakat. Investasi pasti membututuhkan lahan-lahan termasuk lahan warga.”
Investasi skala besar, katanya, juga berpotensi merusak lingkungan jika tak terkelola dengan baik. Sedang tak ada sanksi jelas bagi perusahaan yang merusak.
“Apalagi pemerintah terkesan mudah memberikan konsesi bagi industri ekstraktif yang rakus lahan dan abai masyarakat sekitar dan lingkungan.”
Asmar mengimbau aparat, sebagai pengayom masyarakat seharusnya melihat resistensi masyarakat sebagai upaya membela hak. Sehingga aparat tidak dibenarkan refresif terhadap aksi-aksi warga terkait pengelolaan sumber daya alam atau peruntukan ruang.
“Seharusnya peran negara dikembalikan dalam fungsi pokok melindungi kepentingan masyarakat dan menegakkan hukum pelindungan lingkungan.”
Grasi Eva Bande sinyal positif
Menurut Kepala Biro Kelembagaan dan Infokom Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, Armansyah Dore, hingga kini HAM masyarakat adat belum ditegakkan. Meski hak ini termasuk dalam kesepakatan internasional dan Indonesia meratifikasi.
Namun, Armansyah menilai ada optimisme dalam pemerintahan Jokowi ini dengan rencana pembebasan Eva Bande, aktivis Banggai.
“Ini tidak saja penting bagi Eva Bande atau petani dan masyarakat adat lain, juga bagi aktivis-aktivis pembela HAM lain.”
Walhi juga menyambut baik komitmen Jokowi memberikan grasi kepada Eva Bande. “Kami mendorong, pemberian grasi juga kepada dua petani lain yakni Arief Bennu dan I Nyoman Swarna, yang dikriminalisasi,” kata Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional.
![]()
Massa pengunjuk rasa tuntut Murad Husain ditangkap dan meminta Eva Bande dibebaskan. Foto: Walhi Sulteng
Walhi berpandangan, grasi Presiden merupakan satu isyarat kepada aparat penegak hukum agar tidak mudah semena-mena merekayasa kasus, hingga mengakibatkan banyak pejuang lingkungan dan agraria dikiriminalisasi.
Momentum ini, katanya, bisa menjadi upaya politik memperkuat dasar hukum bahwa pejuang lingkungan hidup dilindungi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurut Abetnego, grasi kepada Eva Bande bukanlah justifikasi bagi pemerintah bahwa Eva Bande telah melakukan kejahatan. “Apa yang dilakukan Eva Bande bersama kawan-kawan petani sebuah jalan perjuangan mendapatkan keadilan atas hak-hak pengelolaan sumber-sumber agraria yang dirampas kekuatan modal dan difasilitasi pemerintah.”
Pemberian grasi ini, katanya, mesti ditempatkan sebagai pembuktian bagi pemerintah mengoreksi sistem hukum yang memberikan legitimasi kepada negara mengkriminalisasi warga berjuang demi keadilan agraria dan lingkungan hidup.
Pada Hari HAM ini, Walhi mendesak negara merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Eva Bande, petani dan semua pejuang yang menjadi tahanan politik (tapol) agraria.
“Rehabiltasi menjadi hak bagi semua pejuang agraria dan lingkungan hidup atas tindakan negara menggunakan kewenangan untuk membukam perjuangan rakyat.”
Pelanggaran HAM Perhutani
Dari Yogjakarta, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa mendesakJokowi menuntaskan pelanggaran HAM di kawasan hutan Perhutani.
Ronald Ferdaus, vocal point KPH Jawa mengatakan, selama ini terjadi dugaan pelanggaran HAM dalam penguasaan hutan Jawa oleh Perhutani dan karakteristik kerja Perhutani.
Berdasarkan catatan ARuPA dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang, dalam kurun 1998-2011, Perhutani telah menganiaya, mencederai, dan menembak setidak-tidaknya 108 warga desa sekitar hutan yang dianggap atau diduga mencuri kayu atau merusak hutan. Sebanyak 34 orang tewas tertembak atau dianiaya petugas keamanan hutan dan 74 lain luka-luka.
“Terdapat 64 kasus penganiayaan dan penembakan. Perhutani juga tak segan mengkriminalisasi warga yang dituduh mencuri kayu.”
Catatan organisasi HuMa tahun 2013, dari 72 konflik kehutanan di Indonesia, 41 terjadi di Jawa , notabene diurus Perum Perhutani. Untuk itu, rekonfigurasi hutan Jawa perlu dalam melestarikan hutan guna memperbaiki keseimbangan ekologi Jawa. Serta perluasan ruang kelola rakyat dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat desa hutan. “Perlu perubahan beberapa aspek penting yaitu paradigma, tata kuasa, tata guna, dan kebijakan.”
Mengenai rekonfiguasi, katanya, hal mendasar paling mendesak tata ulang persoalan tata kuasa lahan hutan Jawa. Sebab, dalam satu dekade terakhir banyak konflik lahan menimbulkan korban jiwa. Untuk menuju realisasi rekonfigurasi ini, kolasi merekomendasikan langkah penting , pertama rekonstruksi kebijakan, mulai dari UU sampai peraturan pelaksana.
“Jika pemerintahan sekarang berkomitmen menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Perhutani, salah satu jalan dengan mencabut PP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani. Terlebih agenda ini tercantum dalam quick win Jokowi–JK,” kata Ronald.
Zainal Arifin dari LBH Semarang mengatakan, sebenarnya antara masyarakat dengan Perhutani dalam pengelolaan hutan dan akses masyarakat bisa terlindungi dengan ada kesepakatan. Namun, kesepakatan itu dilanggar Perhutani, dan masyarakat tetap tidak punya kases masuk hutan.
Data LSM AruPa menyebutkan, ada 8,7 Juta penduduk miskin di desa Jawa. Dari 5.400 desa hutan, 60% desa miksin & tertinggal. Penguasaan lahan 1993 sekitar 0,3 hektar dan tahun 2012 sekitar 0,1 hektar.
Deforestari hutan terus terjadi di Jawa. Dari 2000-2009, tutupan hutan Jawa turun 61%. Dari 2,2 juta hektar menjadi 0,8 juta hektar. Sedangkan tegakan hutan, 1998-2007, kayu Jati menurun dari 36,2 juta menjadi 18,9 juta meter kubik dan diprediksi 2017 habis.
Kondisi ini akan berdampak pada bencana ekologis. Catatan BNPB, pada 2013, sebesar 82,4 % Jawa berisiko banjir, 20,8% longsor. Sedangkan 2012-2013, terdapat 1.368 bencana, merenggut 280 jiwa dan 256.892 terpaksa mengungsi.
Jokowi, Selasa, (9/12/14) di Gedung Agung, Yogyakarta dalam peringatan hari HAM ini menyampaikan, pemerintahan berkomitmen menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia secara berkeadilan. Jokowi mengaku memegang teguh dalam rel konstitusi atau UUD 1945 yang jelas memberikan penghargaan terhadap HAM sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pelaksanaan hak asasi manusia tidak sekadar penegakan hukum juga mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,” kata Jokowi dalam sambutan.
![]()
Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam. Sayangnya, kebijakan pemerintah malah menyuburkan impor. Lebih parah lagi, para petani, pekebun (produsen pangan kecil) malah banyak tersingkir dari wilayah kelola mereka karena desakan atas investasi skala besar. Foto: Sapariah Saturi
Tuntutan pemenuhan hak pangan
Sementara itu Aliansi untuk Desa Sejahtera pada Hari HAM ini mengingatkan, pemerintah mengenai pemenuhan hak pangan.
Dalam 10 tahun, pemerintah abai terhadap hak pangan rakyat, yang ditandai impor pangan meningkat, harga pangan sulit terjangkau masyarakat miskin, 5 juta lebih penghasil pangan berkurang.
Tuntutan aliansi ini, pemerintahan Jokowi wajib segera memenuhi hak atas pangan, hak dasar tiap manusia dan memenuhi janji dalam Nawa Cita.
Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera dalam rilis mengatakan, tidak semudah membalik telapak tangan memenuhi hak atas pangan di tengah situasi serba krisis dan terbatas ini.
Dia mengatakan, negara mempunyai peran penting karena memiliki otoritas dan kapasitas dalam mengkonsolidasikan sumberdaya ekonomi dan politik demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan.
“Negara wajib menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat terutama para produsen skala kecil dan konsumen dalam negeri.”
Selama ini, katanya, pemerintah tidak serius menegakkan pemenuhan hak atas pangan, dengan pilihan kebijakan yang menyebabkan kondisi pangan terus memburuk. “Langkah awal Jokowi-JK menjadi penting sebagai dasar membenahi kondisi darurat pangan ini,” katanya.
Dia mencontohkan, langkah Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, ingin membenahi nasib petani garam, belum mendapatkan dukungan cukup bahkan keterbukaan dari kementerian lain. “Harusnya ini segera dibenahi, koordinasi antara kementerian terkait, karena impor garam merugikan rakyat kecil khusus petambak garam kecil.”
Hal sama terjadi pada pemenuhan daging sapi, niat ingin swasembada, tetapi diawali rencana menerbitkan izin impor 264 ribu sapi pada kuartal keempat 2014. “Sudah seharusnya dipikirkan sejak awal peta jalan kedaulatan pangan Indonesia.”
Ahcmad Surambo, dari Pokja Sawit mengingatkan lagi pusat kedaulatan pangan adalah kesejahteraan produsen pangan skala kecil. Menurut dia, pertarungan bukan hanya berapa banyak luas tanaman pangan yang dipertahankan atau dicetak, tetapi jenis tanaman apa yang didukung tumbuh, bagaimana benih dan berbagai asupan lainnya disediakan. “Apakah petani harus tergantung lagi, atau ada langkah lain yang menjamin kebebasan petani menghasilkan pangan berkelanjutan?”
Situasi saat ini, katanya, dengan penolakan gugatan masyarakat sipil terhadap UU Pangan, terkait benih transgenik menunjukkan arah salah dalam meletakkan landasan kedaulatan pangan.
Begitupula rencana tiap tahun membangun bendungan, lima sampai tujuh, atau sekitar 25-35 bendungan dalam lima tahun, kata Achmad, harus benar-benar memperhitungkan berbagai aspek. “Bukan hanya teknis, juga lingkungan, sosial dan pendanaan. Proyek-proyek besar harus membawa kesejahteraan bagi produsen pangan skala kecil, bukan sebaliknya.”
Dari Hari HAM: Tuntutan Pemenuhan Hak Hidup, Pangan dan Lingkungan Sehat was first posted on December 10, 2014 at 11:48 pm.