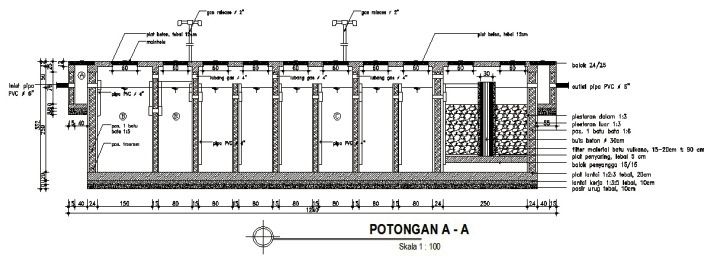![Aksi di Hair Tani di Jakarta, salah satu menuntut reforma agraria. Foto: Sapariah Saturi]()
Aksi di Hari Tani di Jakarta, salah satu menuntut reforma agraria. Foto: Sapariah Saturi
M Daris menarik nafas panjang kala mulai menceritakan nasib yang dia alami. Setelah kampung menjadi waduk, dia tak memiliki lahan lagi buat bertani. Kini dia tinggal di Kampung (relokasi) Leweng, di Sumbawa, tak jauh dari waduk yang dibuat pemerintah. Pria paruh baya ini bertani menggarap lahan di sekitar rumah. Di sana, dia menanam jati, jambu mente dan randu. Di bawah pepohonan itu juga ditanami padi.
Nasib buruk menghampiri, lahan tani itu ternyata menurut pemerintah masuk kawasan hutan lindung. Kala tanaman berusia sekitar tiga tahun, dan hampir berbuah, petugaspun datang mencokok dengan tuduhan merambah kawasan hutan. Tak hanya Daris, empat petani lain juga mengalami nasib sama.
“Saya tanam jati, jambu mente. Saya tak merusak hutan. Itu ladang dari dulu jadi kami tanami, tapi katanya kawasan hutan. Kami ditangkap,” katanya, kala saya berkunjung ke kampung itu, pekan lalu.
Dia divonis delapan bulan penjara pada 2011. Kini, Daris sudah keluar dari penjara, tetapi bukan lepas dari penderitaan karena lahan bertani tak ada.
Nasib serupa Daris dialami ribuan bahkan jutaan warga petani di Indonesia di berbagai daerah. Mereka tak bisa bertani karena berhadapan dengan pemerintah maupun pengusaha. Ketimpangan penguasaan lahan begitu besar di negeri ini. Tak pelak, konflik agraria terjadi di mana-mana.
Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 10 tahun (2004-2014), periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi 1.391 konflik agraria di Indonesia, dengan areal seluas 5.711.396 hektar. Terdapat lebih 926.700 keluarga menghadapi ketidakadilan agraria.
Berdasarkan sektor, konflik agraria di perkebunan 536 kasus, infrastruktur 515, kehutanan 140, tambang 90, pertanian 23, dan pesisir-kelautan enam kasus.
Ketidakberpihakan pemerintah menimbulkan intimidasi dan kriminalisasi. Cara-cara represif oleh kepolisian dan militer pun terjadi hingga menimbulkan banyak korban petani dan komunitas adat. Selama periode itu, sekitar 1.354 orang ditahan, 553 luka-luka, 110 tertembak aparat, serta 70 orang tewas.
Bertepatan dengan Hari Tani pada Rabu (24/9/14) ini, reforma agraria pun menjadi tuntutan utama dalam peringatan di berbagai daerah.
![Ribuan para petani turun di Jakarta meneriakkan ketidakadilan yang mereka alami selama ini. Foto: Sapariah Saturi]()
Ribuan para petani turun di Jakarta meneriakkan ketidakadilan yang mereka alami selama ini. Foto: Sapariah Saturi
Di Jakarta, ribuan massa petani dan organisasi tani aksi di depan Istana Negara. Para petani dari Bogor, Garut, Subang, Karawang dan daerah-daerah lain berkumpul meminta keadilan pemerintah. Bahkan, sebagian rela dari jauh-jauh membawa anak-anak dan bayi mereka.
“Bagikan tanah untuk buruh tani dan petani miskin.” “Ayo bentuk Kementerian Agraria.” “Selesaikan konflik agraria.” “JKW-JK wujudkan keadilan agraria.” “Hapuskan MP3EI.” “Bebaskan petani dan perjuang agraria. Setop kriminalisasi.” “Tuntut pelaksanaan land reform.” “Tanah untuk rakyat.” Itulah antara lain spanduk dan poster yang dibawa dalam aksi itu.
Mereka meminta, pemerintah SBY pada sisa kekuasaan bisa menjalan reforma agraria. Presiden baru, Joko Widodopun diingatkan agar memenuhi janji menjalankan reforma agraria ini.
“Saya mau bertani dengan aman, tak khawatir tanah diambil pengusaha,” kata Wati, petani dari Pabuaran, Subang, Jawa Barat.
Dia mendengar kawasan itu sudah diincar investor. Itulah yang menjadi kekhawatiran warga saat ini. Dia mempunyai lahan sawah sekitar 4.000 meter dengan tanam padi setahun sekali, penghasilan sekitar 15 kwintal. “Sawah pakai tadah hujan. Jadi, bisa setahun sekali. Kalau sudah kemarau gini ya kerja apa aja. Ada yang jadi buruh tani, ada juga beternak.” Mereka sudah bersyukur jika bisa hidup dan bertani dengan aman.
Iwan Nurdin, sekretaris jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan, era SBY reforma agraria tak berjalan. Yang terjadi, malah perampasan lahan-lahan pertanian oleh perusahaan dibantu tangan-tangan pemerintah dan aparat. “Sawit banyak merampas tanah petani, TNI/Brimob menjaga perusahaan pun menangkapi petani.”
Merekapun menyambut baik jika pemerintahan baru ini hendak menjalankan reforma agraria. Untuk itu, katanya, pemerintahan baru harus membentuk Kementerian Agraria dan merealisasikan tanah-tanah buat petani miskin agar hidup layak. Pemerintah, katanya, juga harus membentuk badan atau komisi khusus penyelesaian konflik-konflik agraria. “Banyak konflik dan perampasan lahan terjadi. Ini harus diselesaikan.”
Pemerintah ke depan, kata Iwan, tak boleh lagi mendiamkan konflik-konflik agraria berlarut dan mengorbankan rakyat. “Pemerintah baru ini jangan sampai mengulangi masalah seperti rezim SBY-Boediono.”
Untuk itu, katanya, harus ada pemulihan hak warga atau petani. Pemerintah juga mesti meminta maaf atas kriminalisasi dan rakyat yang sudah menjadi korban.
![Band Marginal juga meramaikan aski Hari Tani di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi]()
Band Marginal juga meramaikan aski Hari Tani di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi
Begitu juga dikatakan Idham Arsyad, koordinator Gerakan Nasional Desa Bangkit. Menurut dia, pelaksanaan reforma agraria pemerintahan Jokowi tak boleh melenceng dari tuntutan masyarakat. Reforma agraria di sini, katanya, pemulihan penguasaan agraria yang timpang selama ini.
“Jokowi diharapkan tak main-main terhadap tuntutan reforma agraria petani ini. Kalau dia mengulangi seperti era SBY, akan berhadapan dengan petani dan organisasi petani.”
Sama juga diungkapkan Andika, pegiat lingkungan dari Sulawesi Tengah. Dia mendesak, pemerintahan baru, Jokowi-JK konsisten menjalankan reforma agraria seperti termaktup dalam visi misi mereka.
Rahmat, sekjen AGRA mengatakan, masa SBY, sekitar 1.000 lebih warga( petani) ditangkap karena berkonflik dengan perusahaan maupun pemerintah. Perampasan lahan tani terjadi di mana-mana. Untuk itu, diapun menuntut Kementerian Kehutanan dibubarkan. “Karena di sanalah terjadi perampasan lahan petani terbesar.”
Munadi Kilkoda, ketua BPH AMAN Maluku Utara (Malut) mengatakan, kehidupan petani terdesak di mana-mana. Di Patani, Halmahera, petani terancam karena lahan adat mereka hendak beralih menjadi sawit. Mereka menolak izin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Hingga kini, perjuangan warga terus berjalan.
Dia berharap, negara memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah leuhur mereka. “Jadi, tanah sumber pertanian yang mereka kelola turun temurun itu bisa terus generasi ke generasi.”
Menurut dia, tanah adat merupakan sumber utama perekonomian warga hingga jangan pernah diberikan izin kepada perusahaan baik tambang, sawit, HTI dan lain-lain. “Karena koperasi massif itu akan mendatangkan efek tidak menguntungkan petani.”
Sejalan dengan reforma agraria, dia mendesak pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Agung No 35 yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara. “Ini untuk melindungi hak masyarakat adat dan tentu petani, bagian dari komponen masyarakat adat.”
Senada diungkapkan Febriyan Anindita, divisi Advokasi AMAN Sumbawa. Dia mengatakan, izin-izin yang diberikan pemerintah yang merampas wilayah adat atau kelola petani menjadi ancaman besar. Tak hanya ancaman petani kehilangan wilayah kelola juga bahaya lingkungan. “Misal, perusahaan hadir, menyebabkan defisit sumber air. Ini sungguh ancaman bagi petani.”
Dia mengatakan, perusahaan masuk ke satu wilayah tak bisa seenaknya, harus ada sosialisasi atau berunding dengan warga untuk memastikan keberlangsungan kelola petani tak terganggu.
Aksi di depan Istana Negara itu juga menyuguhkan aksi teartikal dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Disitu menceritakan lahan petani hangus, terampas, berkat izin-izin dari pemerintah kepada perusahaan. Aparatpun sigap menjaga bisnis itu dengan menjadikan petani subyek tangkapan.
Band Marginal yang dimotori Mike pun tampil dengan menyanyikan beberapa lagu antara lain Negeri Ngeri dan Hukum Rimba. Terik matahari yang menyengat pun seakan tak terasa, bahkan makin menyulutkan semangat petani menyuarakan tuntutan keadilan bagi mereka.
![Selama ini, banyak lahan tani terampas dan rumah-rumah mereka digusur. Foto: Sapariah Saturi]()
Selama ini, banyak lahan tani terampas dan rumah-rumah mereka digusur. Foto: Sapariah Saturi
Perampasan lahan di berbagai daerah
Di Palembang, Sumatera Selatan, aksi Hari Tani dimulai longmarch dari Walhi menuju DPRD Sumsel. Massa dari gabungan Serikat Petani Sriwijaya, Mahasiswa Hijau Indonesia, Walhi, AMAN, SHI, dan Front Mahasiswa Nasional Palembang lalu bergerak kantor BPN terakhir kantor gubernur.
Dedek Chaniago, koordiantor aksi meneriakkan tuntutan kepada pemerintah daerah dan pusat. Pertama, membebaskan enam petani dan tokoh adat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Kedua, pembaruan agraria di Sumsel dengan penyediaan dan perlindungan tanah untuk petani dan masyarakat adat di Desa Air Sugihan (OKI), dan Desa Sinar Harapan, Telang, Simpang Bayat, Pangkalan Bayat, Dawas, dan Pangkalan Tungkal (Kabupaten Muba).
Ketiga, penyelesaian konflik agraria di Sumsel berasas keadilan petani dan masyarakat. Keempat, meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada petani dalam mengelola tanah. Antara lain, melalui akses permodalan dengan pengembalian bertahap dan pengembangan infrastruktur pertanian dengan bantuan teknologi serta sarana produksi pertanian.
Kelima, menuntut peningkatan harga jual karet petani melalui perlindungan harga dan tata niaga karet. Keenam, menuntut penghentian penangkapan, intimidasi, dan teror, terhadap petani, masyarakat adat, dan pejuang agraria. Juga menghentikan keterlibatan TNI/POLRI dalam konflik agraria.
Ketujuh, mendesak gubernur, bupati, walikota, DPRD Sumsel reforma agraria sejati dan membuat peraturan daerah berpihak kepada kepentingan petani dan masyarakat adat. Kedelapan, Presiden baru melaksanakan pembaruan agraria sejati di Indonesia.
Anwar Sadat, Sekretaris Jenderal SPS mengungkap, selama ini pemerintah tidak serius menjalankan reforma agraria. “Pemerintah seharusnya berpihak pada rakyat, melindungi tanah rakyat yang diancam kepentingan komersial dan imperisalis.”
Alex Noerdin, Gubernur Sumsel memastikan tuntutan mereka segera ditindaklanjuti. “Saya memahami tuntutan itu. Saya pastikan, segera ditindaklanjuti,” kata Alex yang menemui sekitar 300-an massa.
![Aksi petani di Sumsel. Foto: Muhammad Ikhsan]()
Aksi petani di Sumsel. Foto: Muhammad Ikhsan
Ribuan petani di Sumut juga memadati jalanan di Medan. Sambil membawa anak-anak dan keluarga, mereka dari berbagai daerah berkumpul memperingati Hari Tani.
Alunan lagu dari masyarakat adat Suku Karo, terdengar riuh ketika mereka berkumpul di Jalan Imam Bonjol, Medan. Tarian Tor-tor, membangkitkan semangat mereka yang sebagian besar tinggal di sekitar dan kawasan hutan ini.
Zubaidah, ketua dewan Pengurus Serikat Petani Indonesia Sumut, menyebutkan, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan terus terjadi. Setidaknya, ada 300 kasus penyerobotan lahan dan konflik lahan, sepanjang 2014.
Terbesar di Langkat, Kota Binjai, menyusul Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Simalungun, Labuhan Batu, Padang Lawas, sampai Mandailing Natal. Semua konflik terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan sawit baik BUMN maupun swasta. Juga konflik antara pemerintah daerah yang merampas lahan adat masyarakat, hingga perusahaan kayu.
“Pemerintah mengabaikan Undang-Undang Pokok Agraria. Pemerintah juga mengabaikan putusan MK. Pemerintah terus memberikan izin perusakan hutan adat untuk jadi perkebunan dan usaha lain.” Kriminalisasi masyarakat adat yang menolak hutan dan lahan dirusak, terjadi. “Kemana keadilan negeri ini?”
Tobu Ginting, ketua Masyarakat Adat dari Desa Silindak, Serdang Bedagai, menceritakan, kriminalisasi Polres Serdang Bedagai (Sergai), terhadap 21 petani yang turun temurun menanam padi, dan perkebunan palawija, karet dan sawit disana.
Ratusan petani dil lahan 225 hektar yang sudah dikuasai dua generasi, dipaksa keluar. Gubuk-gubuk dibakar, ada yang diseret dan dimasukkan ked truk polisi. Setidaknya ada 21 ditahan, dan 50 kendaraan petani disita.
“Kami diusir dari lahan yang sudah kami miliki lengkap dengan surat-surat, hanya agar PTPN II dan perkebunan sawit bisa mengambil alih lahan kami.” “Tolong anggota DPRD terhormat, bantu kami,” katanyaberkaca-kaca.
“Sekarang kami tergusur, hidup miskin. Kami tetap berjuang hak kami kembali sampai mati.”
Dian Arif, dari SPI Sumut mengta. Dia mengatakan, tidak jelasnya proses kepemilikan lahan, menyebabkan konflik yang terjadi terus menerus.
![Kriminalisasi masyarakat adat dan petani yang mempertahankan lahan, menjadi kisah dalam peringatan hari tani nasional di Sumut. Foto: Ayat S Karokaro]()
Kriminalisasi masyarakat adat dan petani yang mempertahankan lahan, menjadi kisah dalam peringatan hari tani nasional di Sumut. Foto: Ayat S Karokaro
Dia menyatakan perlu dilakukan penginventarisasi kasu-kasus tanah melibatkan masyarakat adat dan kelompok tani, agar ada keterbukaan, sehingga konflik bisa terselesaikan.
Syahmanan, masyarakat adat dari Kabupaten Asahan, menyatakan, lahan adat mereka seluas 350 hektar di Bandar Pasir Mandoge, direbut paksa PT Sinuraya, kini menjadi PT Doge-Doge. Tiga petani tengah bercocok tanam, diculik dan dianiaya. Rumah mereka dihancurkan.
“Ketika kami Tanya ke BPN Asahan, mereka memberikan penegasan perusahaan itu tidak memiliki izin. Cara mereka melibatkan oknum aparat, membuat kami tersingkir. Kembali, keadilan tak berpihak pada kami.”
Azib Syah, ketua sementara DPRD Sumut, menegaskan, dalam waktu dekat akan memprioritaskan menyelesaikan masalah ini. Aparat penegak hukum, diminta tak semena-mena terhadap petani.
“Kita akan bawa kasus ini dalam paripurna dewan. Akan membentuk tim khusus menangani. Jangan ada lagi kriminalisasi petani dan masyarakat adat.”
Soroti MP3EI
Hari Tani di Sulawesi Selatan, menyoroti masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang dicanangkan SBY.
Asmar Eswar, direktur Walhi Sulsel, mewakili Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria pada Hari Tani, di anjungan Pantai Losari Makassar mengatakan, program ini menimbulkan krisis multi dimensi, baik secara ekonomi, sosial dan ekologis. Megaproyek ini dinilai makin membebani masyarakat dan kaum tani di Indonesia.
Menurut Asmar, dalam beberapa tahun terakhir, praktik-praktik monopoli sumber-sumber agraria makin massif dan diperparah kehadiran MP3EI.
![Di Sulsel, aksi Hari Tani juga menuntut beberapa hal, salah satu menghentikan kriminalisasi petani. Foto: Wahyu Chandra]()
Di Sulsel, aksi Hari Tani juga menuntut beberapa hal, salah satu menghentikan kriminalisasi petani. Foto: Wahyu Chandra
“Terjadi peningkatan konflik agraria siginifikan dan menyengsarakan rakyat kecil dan petani.”
Beberapa kasus perampasan tanah di Sulsel antara lain tanah adat Ammatoa Kajang di Bulukumba oleh PT London Sumatera (Lonsum), PTPN XIV vs petani di Luwu Utara, Wajo dan Takalar.
Kasus lain, perampasan lahan adat Koronsi’e Dongi oleh PT Vale di Tanah Luwu, perjuangan petani di Malili, Luwu Timur melawan PT Sindoka. Masyarakat sekitar kawasan karst Maros dan Pangkep melawan Bosowa, Semen Tonasa dan sejumlah korporasi tambang lain.
Aliansi menyampaikan tuntutan , antara lain pembentukan Kementerian Agraria, tolak RUU Pertanahan yang akan menggantikan UUPA 1960, membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria, land reform atau redistribusi lahan.
Sardi Razak, ketua BPH AMAN Sulsel, berharap, pemerintahan baru memberi perhatian terhadap berbagai kasus kriminalisasi masyarakat adat dan petani. Dia mencontohkan, penangkapan dan teror pemerintah serta aparat kepada komunitas adat Barambang Katute, Sinjai ataupun Matteko di Gowa.
Aksi bersama ini mecuri perhatian warga, apalagi diselingi aksi teatrikal perampasan tanah warga disertai kekerasan, dilakukan pemerintah dan penguasa dan mendapat sokongan aparat keamanan.
Dari Sulawesi Tengah, Eva Bande, pejuang petani yang kini mendekam di dalam penjara menulis surat.
“Hari itu bagiku adalah peringatan atas ketertindasan petani, bukan peringatan hari kebangkitan kaum tani. Bukan pula pernyataan penghargaan atau pengakuan negara untuk memerdekakan petani dari ketertindasan mereka berabad-abad.” begitu bunyi surat Eva.
Menurut dia, sejarah bergerak silih berganti melalui titian waktu, berganti generasi, berganti rezim penguasa. “Tetapi satu yang tidak berubah, nasib kaum tani.”
Di era yang merdeka yang maju ini, kaum tani tetap hidup dalam penindasan tak tampak. Mereka hidup di sekeliling kekayaan alam tetapi miskin. “Tanah mereka semakin sempit, mereka makin tak berdaya, karena kemerdekaan lebih dinikmati kaum kaya, kaum pelajar, anak-anak kaum bangsawan.”
Kedaulatan Pangan
Kembali ke Pulau Jawa, di Surabaya, puluhan petani dan aktivis lingkungan tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur, berunjukrasa di depan Grahadi. Mereka mengangkat tema Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Pangan untuk Kemandirian Bangsa.
![Aksi teatrikal Hari Tani di Surabaya, menceritakan penderitaan yang dialami petani, yang terpinggir dan menderita. Foto: Petrus Riski]()
Aksi teatrikal Hari Tani di Surabaya, menceritakan penderitaan yang dialami petani, yang terpinggir dan tergusur oleh kepentingan pemilik modal. Foto: Petrus Riski
Sambil membentangkan spanduk dan poster berisi aneka macam tuntutan, para petani mendesak pemerintah melakukan reformasi agraria dan mengembalikan kedaulatan pangan karena selama ini dikalahkan produk impor.
“Kembalikan kedaulatan pangan, jangan sampai terus dijajah impor. Dulu kita mempunyai semua, kenapa sekarang tergantung negara lain,” kata Sugiono, koordinator lapangan.
Syaiful Zuhri, ketua SPI Jatim mengatakan, penyusutan lahan pertanian terjadi di Jatim, salah satu penghasil padi nasional.
Menurut dia, rata-rata 1,1 juta hektar pertanian irigasi, berubah fungsi. Catatan BPS 2013, ada sekitar 1.500-an hektar beralih fungsi, menjadi perumahan, jalan raya, dan bangunan.
Dia menuturkan, penurunan rumah tanga petani dari 31,23 juta menjadi 26,14 juta pada 2013, menyusut 16 persen dalam 10 tahun terakhir.
Di Indonesia, kelompok petani di bawah 34 tahun, berkisar 12,88 persen (3,36 juta), dari total 26,14 juta rumah tangga petani. Petani diatas 34 tahun 87,14 persen. Sensus pertanian 2013 menyebutkan, mayoritas petani di Indonesia petani kecil atau gurem, dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang 0,5 hektar. Dari 26,14 juta rumah tangga petani, 14,62 juta (56,12%) adalah petani gurem.
“Kondisi ini tidak dapat dilepaskan kepemilikan lahan petani yang timpang.”
Konflik petani atau masyarakat adat, masih menjadi persoalan. Ubed, koordinator KPA Jatim mengatakan, ada 36 konflik agraria di sana, melibatkan petani dengan perkebunan.
Selama ini, petani mengelola lahan yang diklaim ‘milik’ perkebunan maupun Perhutani. Mereka menanam tanaman pangan dan produksi, tanpa merusak maupun mengubah fungsi lahan. Bahkan petani ikut menjaga dan melestarikan hutan maupun perkebunan, dari bahaya kerusakan maupun pencurian kayu. Upaya menanami lahan di tengah krisis lahan, semata untuk memperoleh manfaat ekonomi petani.
“Sekarang ini lahan dikelola, ditanami berbagai macam bentuk tanaman, ada model petani di pinggir hutan, wana tani, ada agroforestri. Konsep pertanian itu juga arif lingkungan sekitar. Juga menjaga ekosistem, konservasi dan menjaga sumber-sumber mata air,” kata Ubed.
Ketua Aliansi Petani Indonesia (API) Jatim, Sugiono mengatakan, dukungan pemerintah di sektor pertanian minim. Pendapatan keluarga petani di bawah standard minimal penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia. Sementara biaya produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian, tidak sebanding dengan harga jual.
Untuk itu, kata Syaiful, mereka pemerintahan Jokowi-Jk, mampu merealisasikan janji politik, akan membagikan 9 juta hektar lahan kepada petani penggarap lahan.
“Kita menuntut dijalankan model pertanian untuk kedaulatan pangan, karena rezim SBY selalu impor. Kami minta, kriminalisasi petani dan kekerasan dihentikan.”
![Di Bali, aksi tani untuk penguatkan kecintaan pangan lokal. Dengan mengganti sampah dengan sayur mayur lokal. Foto: Luh De Suriyani]()
Di Bali, aksi tani untuk penguatkan kecintaan pangan lokal. Dengan mengganti sampah dengan sayur mayur lokal. Foto: Luh De Suriyani
Konsumsi produk lokal
Di Bali, Hari Tani diperingati dengan cara kreatif oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar. Puluhan warga menukar tiga botol plastik bekas dengan satu bungkus sayuran lokal.
Mereka ingin mengampanyekan hasil pertanian lokal karena pasar diserbu impor. “Salah satu cara menyelamatkan pertanian dengan konsumsi produk lokal,” kata ketua Badan Eksekutif Mahasiswa I Dewa Gede Wipa Wira Utama.
Tak hanya mahasiswa yang tertarik sistem barter ini, juga pemulung dan pengelola kantin sekitar kampus. Mereka mendapatkan tiga sayuran yakni sawi, buncis, dan wortel. Semua dipasok dari lahan pertanian mahasiswa di pusat budidaya sayuran Bali, Baturiti, Tabanan.
Di Bali, Hari Tani tak mendorong kelompok tani turun ke jalan menyampaikan keluhan. Padahal, pariwisata Bali dihidupi oleh budaya agraris, misal subak, seni tari, ritual, dan lain-lain. Sawah kini makin bak kosmetik. Hadir buat memulas keindahan hotel, villa, restoran.
Kenyataan, petani makin berkurang. Hasil sensus pertanian terakhir di Bali, sekitar 700 rumah tangga pertanian berkurang tiap bulan, termasuk perkebunan dan peternakan.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bali IB Wisnu Wardhana tak terlalu khawatir. Menurut dia, ini konsekuensi logis tumbuh pariwisata dan usaha kecil menengah di Bali. “Kedua sektor menyumbang pendapatan terbesar.”
Menurut dia, indikator keberhasilan bukan jumlah petani tetapi produktivitas pertanian. “Dengan mekanisasi pertanian, produktivitas ditingkatkan.” Alih fungsi lahan pertanian produktif terjadi.
Dalam Kongres Kebudayaan Bali 2013 tentang budaya subak dan pertanian juga dibicarakan mengenai lahan, generasi pertanian, dan revitalisasi subak yang menurun.
![Ribuan petani datang ke Jakarta dari beberapa daerah. Mereka aksi di depan istana Negara menuntut keadilan karena selama ini terpinggirkan oleh kepentingan pengusaha dan pemerintah. Mereka rela datang dari jauh-jauh bahkan membawa anak-anak mereka. Foto: Sapariah Saturi]()
Ribuan petani datang ke Jakarta dari beberapa daerah. Mereka aksi di depan istana Negara menuntut keadilan karena selama ini terpinggirkan oleh kepentingan pengusaha dan pemerintah. Mereka rela datang dari jauh-jauh bahkan membawa anak-anak mereka. Foto: Sapariah Saturi
![Dalam aksi tani di Jakarta, pemerintahan baru, Jokowi-JK dituntut menjalankan keadilan agraria. Foto: Sapariah Saturi]()
Dalam aksi tani di Jakarta, pemerintahan baru, Jokowi-JK dituntut menjalankan keadilan agraria. Foto: Sapariah Saturi
![MP3EI, salah satu program SBY yang banyak menyebabkan petani tergusur. Foto: Sapariah Saturi]()
MP3EI, salah satu program SBY yang banyak menyebabkan petani tergusur. Foto: Sapariah Saturi
Hari Tani: dari Ketimpangan Penguasaan Lahan hingga Kemandirian Pangan was first posted on September 24, 2014 at 11:43 pm.