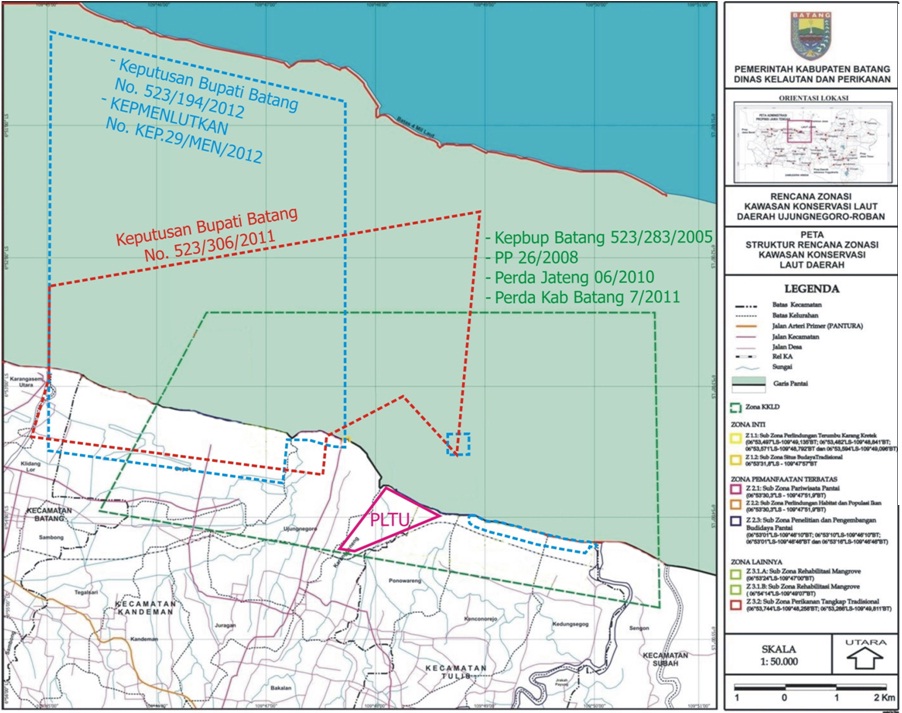Tandan buah segar sawit milik perusahaan besar di Sumut, perluasan bisnis mereka menyebabkan deforstasi. Foto: Ayat S Karokaro
Tiga organisasi lingkungan di Indonesia, yaitu Greenpeace, Walhi dan Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS), mendesak pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kala, mengevaluasi izin perluasan kebun sawit di kawasan hutan. Tujuannya, menekan laju deforestasi hutan di Indonesia, terlebih di perkebunan sawit cukup luas, seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Utara. Demikian pernyataan bersama mereka di Medan, Sabtu (30/8/14).
Mansuetus Darto, koordinator SPKS, mengatakan, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi tidak memperhatikan regulasi. Padahal, dalam UU perlindungan dan pemberdayaan petani, jelas diatur. Untuk itu, pemerintahan baru perlu membangun peta jalan petani (roadmap) hingga bisa menekan deforestasi.
Dengan roadmap ini, pemberdayaan seperti pendanaan dan penguatan kapasitas petani bisa berjalan dan diatur jelas. Bukan, sebaliknya seperti selama ini regulasi bak dipegang perusahaan swasta.
Dia mengatakan, hampir 40% perkebunan sawit milik petani mandiri. Untuk itu, Jokowi-JK diharapkan bisa memberdayakan petani mandiri yang masih memegang teguh adat perlindungan hutan. Jokowi-JK harus bisa meningkatkan produktivitas sawit yang nol deforestasi. Bukan seperti milik perusahaan besar bahkan BUMN yang merusak hutan. Dia menyebutkan, ketimpangan pengetahuan, dan dukungan pemerintah minim, menyebabkan produktivitas kebun sawit mandiri rendah.
Sisi lain, pemerintah menargetkan produksi sawit nasional dari 25 juta ton menjadi 40 juta ton pada 2020. Kondisi ini, berisiko mempercepat deforestasi hutan.
“Harus ada aturan tegas mencapai nol deforestasi, bersikap tegas terhadap perusahaan besar yang melanggar, dan pembangunan roadmap kepada petani mandiri,” ucap Darto.
Berdasarkan pemantauan mereka, deforestasi terjadi oleh perusahaan besar. Terbukti, banyak perusahaan sawit melanggar regulasi. Sesuai aturan, jika memiliki perkebunan sawit di atas 25 hektar, harus memiliki izin usaha. Di bawah 25 hektar, hanya wajib memiliki surat tanda daftar budidaya (STDB). “Itu dilanggar bahkan ada meluaskan lahan usaha sampai kawasan hutan.”
Achmad, koordinator Solusi Greenpeace Indonesia, melihat, bukan hanya perusahaan besar perlu kampanye nol deforestasi, juga petani. Untuk itu, best management practice petani mandiri, menjadi salah satu solusi, dimana poin-poin pengelolaan lingkungan ramah, terutama di lokasi gambut berjalan baik. Roadmap petani sawit juga perlu dibuat. “Ini akan mencegah nol deforesrtasi dan berpihak kepada ekonomi berdikari.”
Selain itu, katanya, moratorium izin hutan dan lahan harus diperkuat. Selama periode ini moratorium lemah, terbukti izin masih bertambah. “Komitmen perusahaan menjaga hutan dan tidak melanggar aturan juga perlu dipertegas.”
Sedangkan Kusnadi Oldani, direktur eksekutif Walhi Sumut, menyatakan, ekspansi kebun sawit perlu ditekan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Juga perlu review ulang konsesi perusahaan karena ada dugaan perluasan konsesi perkebunan sawit pemberian izin.
Pemerintah baru, katanya, harus mengeluarkan konsesi bermasalah bagi masyaraat adat. “Begitu luas kerusakan hutan akibat alih fungsi menjadi perkebunan sawit, rezim baru mesti audit lingkungan.” Untuk itu, Walhi Sumut mendesak rezim Jokowi-JK, menghentikan pemberian izin kebun baru kepada perusahaan yang mengabaikan soal lingkungan.

Kebun milik petani sawit mandiri. Perlu keseriusan pemerintah meningkatkan produktivitas petani sawit mandiri dan menyiapkan roadmap buat mereka. Foto: Ayat S Karokaro
Banyak PR
Greenpeace menilai pekerjaan rumah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bidang lingkungan menumpuk dalam 100 hari terakhir hingga menjadi tugas lanjutan bagi pemimpin baru. Greenpeace Indonesia menggambarkan itu lewat empat film dokumenter bertajuk Silent Heroes.
Empat film ini menceritakan pencemaran lingkungan di Kali Ciliwung, masyarakat Sei Utik, Kapuas Hulu, Kalbar, yang mempertahankan kearifan lokal dan tak mendapatkan listrik pemerintah. Lalu, cerita masyakarat Pandumaan-Sipituhuta yang berjuang mempertahankan hutan kemenyan dari perusahaan. Satu lagi, cerita Mama Dian, dari Pulau Bangka, yang berjuang dan tak gentar menolak tambang yang bakal mengeruk pulau mereka.
Arifsyah Nasution mengatakan, juru kampanye Greenpeace Indonesia mengatakan, pemerintahan SBY meninggalkan banyak persoalan lingkungan menyangkut perlindungan hutan, keadilan energi, pencemaran air sungai, serta penangkapan ikan berlebih dan ilegal. “Apabila tak segera diselesaikan, akan menjadi tambahan pekerjaan rumah pemerintahan baru,” katanya dalam rilis kepada media.
Menurut Arifsyah, solusi ketidakadilan energi ini bisa lewat pengembangan sistem energi terdesentralisasi sesuai potensi sumber daya masing-masing daerah, dan mempertimbangkan kearifan lokal. Ini sudah dikembangkan di Sui Utik melalui program energi terbarukan nusantara (enter nusantara) diinisiasi Greenpeace bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Pemerintah, katanya, juga masih tak peduli terhadap sumber daya air sebagai kebutuhan pokok manusia. Pemerintah belum melihat air sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. “Regulasi dan penegakan hukum lemah hingga membuat mayoritas sungai di Indonesia tercemar limbah domestik dan B3 industri.”
Untuk itu, sudah saatnya pemerintah mengubah kebijakan agar tekanan terhadap masyarakat tidak berlarut-larut. Sebelum habis masa jabatan, SBY diminta melakukan langkah nyata. “Pemerintah baru harus bersiap dengan tumpukan pekerjaan rumah ini.”
Berharap kepada Jokowi
Ketua Dewan Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumsel sekaligus Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi mengatakan, dalam visi misi Presiden terpilih Jokowi jelas memasukkan komitmen melindungi dan mengakui keberadaan hak masyarakat adat.
Untuk itu, AMAN berharap, Jokowi bisa merehabilitasi massal masyarakat adat yang dikriminalisasi, termasuk di Sumsel. Sekaligus mendorong dialog antara pemerintah daerah, gubernur, bupati dengan penegak hukum. “Agar mengambil kebijakan implementatif mengakui keberadaan dan perlindungan masyarakat adat,” Senin (1/9/14).
Dia mengatakan, pasca keputusan MK No 35, seharusnya pihak berwenang mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak mengkriminalisasi masyarakat adat akibat berbeda pandangan terhadap hutan.
Pemerintah mengklaim kawasan itu hutan negara. Sedang masyarakat adat adalah hutan adat turun menurun. “Mereka ditangkap disangka mencaplok hutan suaka margasatwa. Kita sangat sesalkan penangkapan itu.”
Menurut dia, setelah keluar MK 35, sudah sepatutnya ada keberpihakkan atas hak-hak adat di Sumsel. “Berikan hak-hak masyarakat adat.”
Koalisi Desak Pemerintahan Baru Serius Tekan Deforestasi dari Perkebunan Sawit. Caranya? was first posted on September 5, 2014 at 4:18 pm.