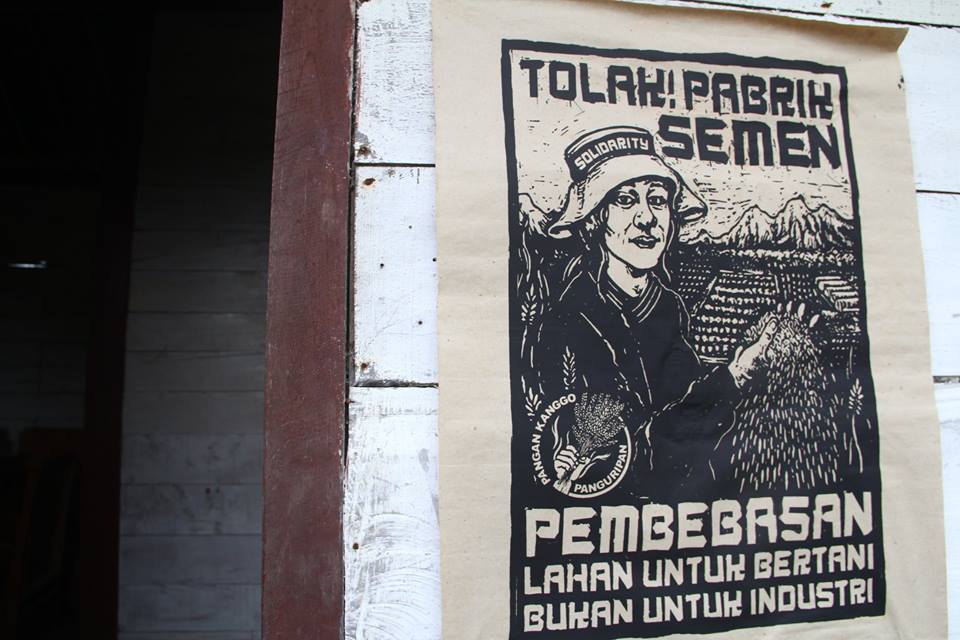![Anak-anak di Kepulauan Wakatobi, sudah belajar dan membantu mengelola rumput laut. Foto: Indra Nugraha]()
Anak-anak di Kepulauan Wakatobi, sudah belajar dan membantu mengelola rumput laut. Foto: Indra Nugraha
Pada Oktober 2013, tiga pelaku pengeboman ikan di perairan Desa Numala Wangi-wangi Selatan, Kepulauan Wakatobi, tertangkap. Ini operasi gabungan nelayan sekitar, petugas taman nasional dan WWF Wakatobi. Pelaku dari Mola Selatan.
“Awalnya ada laporan masyarakat, ada pengeboman. Kita langsung kejar menggunakan speed boat. Mereka berpencar dan berusaha melarikan diri. Satu dari mereka sudah tua, coba melarikan diri menggunakan sampan,” kata Made, staf Taman Nasional Wakatobi (TNW) seksi I, akhir Mei lalu.
Dua pelaku tertangkap. Barang bukti satu botol berisi bahan peledak diamankan. Namun, mereka melarikan diri. Baru tertangkap saat Festival Baju. Ketiganya divonis delapan bulan penjara.
Kini, masyarakat antusias bekerjasama. “Balai taman nasional mendapatkan banyak informasi dari mereka. Jika ada laporan, langsung ditindaklanjuti.”
Dia mengatakan, kesadaran masyarakat menjaga ekosistem laut sangat tinggi. Konsep perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan diterapkan. Di SD, SMP dan SMA para pelajar Wakatobi mendapatkan mata pelajaran tambahan, konservasi.
Para nelayan kini bahu membahu menjaga kawasan laut. Patroli rutin dilakukan kelompok nelayan swadaya dan sukarela. Praktik pengeboman, bius dan penangkapan ikan dalam over fishing berkurang. Mereka sadar, kerusakan ekosistem laut membuat tangkapan ikan berkurang drastis.
Lajuma, ketua kelompok nelayan Lagundi 1, kepulauan Wangi-wangi Wakatobi mengatakan, kesadaran masyarakat sekitar menjaga kelestarian ekosistem laut sudah tinggi.
Dia mengatakan, pengawasan kawasan laut secara berkala oleh warga dan sukarela. Mereka sadar, kawasan laut adalah harta tak ternilai.
“Kita tak mungkin nunggu aparat bertindak. Kalau bukan kita siapa lagi? Orang lain belum tentu mau dan bisa. Meski teror dari luar yang sering ngebom ikan ada tetapi kami bertekad mengamankan,” katanya.
![Kesibukan petani rumput laut. Foto: Indra Nugraha]()
Kesibukan petani rumput laut. Foto: Indra Nugraha
Hal serupa terjadi di Pulau Kaledupa. Kelompok nelayan di pulau itu, Forum Kaledupa Toudani, berperan aktif menjaga kawasan laut.
“Awal 2000, kami gelisah karena marak pengeboman dan pembiusan ikan. Bahkan ada banyak aparat ikut bermain memasok bahan bom dan bius ikan,” kata Edi Jaimu, sekretaris Forkani.
Dia mengatakan, kegelisahan ini mendorong warga Kaledupa membuat organisasi fokus menjaga lingkungan. Pada 2002, terbentuklah Forkani. Organisasi ini mewakili 25 desa di pulau itu.
“Kita sosialisasi di tiap desa mengenai bahaya pakai bom dan bius dalam tangkap ikan. Ini juga dibantu oleh WWF dan TNC. Warga dibantu pengembangan kapasitas dan pengetahuan soal perikanan berkelanjutan lewat berbagai pelatihan,” katanya.
Mereka juga aktif berkoordinasi dengan Balai TNW, misal, penentuan batas zonasi, mereka aktif memberikan saran.
Tahun 2007, mereka bekerjasama dengan Darwin Initiative mengadakan penelitian mengenai ikan karang selama tiga tahun. Hasilnya, ikan karang yang ditangkap nelayan waktu itu 40% dewasa dan 60% anakan. Seharusnya, ikan kecil tak boleh ditangkap, agar populasi tak menurun drastis.
“Kita berharap, pemerintah bertindak menjaga populasi ikan karang. Kontribusi taman nasional masih kurang dan belum banyak dirasakan. Begitupun dalam pengawasan, kurang. Kelompok-kelompok dampingan mengawasi swadaya,” kata Edi.
Saat mereka melaut jika melihat ada sesuatu mencurigakan, langsung melapor kepada pimpinan kelompok. Setelah itu, mereka berkoordinasi dengan Balai TNW.
“Pernah ada yang mengambil karang. Kita kejar dengan sampan agar karang dikembalikan. Begitu juga penambang pasir, kita kejar.”
Namun, saat ini mereka keluhkan sikap nelayan dari luar Kepulauan Wakatobi masih menggunakan cara-cara tak ramah lingkungan. Pengeboman dan pembiusan ikan masih ada.
Mereka juga bekerjasama dengan pihak desa untuk menerbitkan perdes penangkapan ikan. Mereka juga kerjasama dengan pengumpul ikan, salah satu Pulau Mas, dengan menerima ikan besar saja.
![Nelayan melaut. Seraya melaut mereka sambil menjaga kawasan dari praktik-praktik merusak lingkungan. Foto: Indra Nugraha]()
Nelayan melaut. Seraya melaut mereka sambil menjaga kawasan dari praktik-praktik merusak lingkungan. Foto: Indra Nugraha
Keterbatasan anggaran
Sugiyanta, project leader WWF Wakatobi mengatakan, pengelolaan TN Wakatobi, belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari aspek perlindungan biodiversiti maupun kesejahteraan masyarakat. Semestinya, patroli dua kali dalam sebulan. Namun, belum bisa dipenuhi karena keterbatasan anggaran Balai TNW.
TNW terdiri dari beberapa zonasi. Diantaranya zona inti 1.300 hektar, zona pemanfaatan bahari 36.450 hektar, dan zona pariwisata 6.180 hektar. Lalu, zona pemanfaatan lokal 804.000 hektar, pemanfaatan umum 495.700 hektar dan zona khusus darat 46.370 hektar. “Sekitar 105 ribu warga tinggal kawasan taman nasional. Ini unik. Karena luas sama dengan Kabupaten Wakatobi.”
Siti Wahyuna, kepala Balai TNW mengatakan, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan terus dilakukan. Dalam pengawasan, masyarakat ikut terlibat aktif. Balai juga aktif mengembangkan wisata Wakatobi.
“Kita tak melarang warga beraktivitas di kawasan taman nasional. Asal tidak merusak. Masyarakat sudah ada sejak awal. Jadi tidak mungkin kita keluarkan. Kita juga membuat program beragam yang melibatkan masyarakat.”
Untuk patroli, Balai seringkali melibatkan masyarakat meskipun juga mempunyai patroli rutin. “Segi anggaran patroli sebenarnya tidak cukup. Ya, dicukup-cukupkan.”
Polhut Balai TNW, Sakaria mengatakan, patroli rutin setiap 10 hari dalam sebulan. Tujuh hari di darat, tiga hari di laut. Untuk patroli gabungan lima kali dalam setahun.
“Untuk patroli ke tempat terjauh terkendala jarak. Kita kekurangan sarana dan personil. Saat ini ada 15 polhut.”
![Keramba-keramba yang dibuat warga dengan tetap memperhatikan usia tangkap ikan. Foto: Indra Nugraha]()
Keramba-keramba yang dibuat warga dengan tetap memperhatikan usia tangkap ikan. Foto: Indra Nugraha
Kredit konservasi
Ada hal menarik lagi dari kelompok nelayan di Pulau Wangi-wangi. Mereka sukarela patroli menjaga perairan laut Wakatobi, juga menggalakkan kredit konservasi. Dalam diskusi bersama para nelayan dan petani rumput laut di Pulau Wang-wangi, mereka berbagi kisah.
“Kita tergantung pada laut. Jadi laut kita jaga betul,” kata Sumarni, bendahara kredit konservasi.
Kredit konservasi dengan harapan warga di Wangi-wangi, lebih peduli kelestarian lingkungan. Sejak 2009, rencana kredit ini tetapi baru terealisasi 2011. Program ini dibina WWF Wakatobi.
“September 2013 sudah jalan. Kalau ada anggota kredit konservasi ikut pelatihan WWF biasa suka dikasih uang honor pengganti transpor. Kita sisihkan sebagian untuk program ini.”
Menurut Sumarni, besaran pinjaman dana tidak boleh lebih dari Rp1 juta. Lama tergantung kesepakatan, maksimal lima bulan.
Setiap anggota harus menjaminkan pohon atau terumbu karang. Mereka wajib menjaga jaminan itu. Pohon tak boleh ditebang. Begitu juga terumbu karang, harus pastikan terbebas dari pengeboman. Ketika pinjaman terlunasi, mereka harus menanam sejumlah pohon baru.
“Kalau di bank kan jaminan BPKB atau surat tanah. Kita jaminan pohon atau terumbu karang. Satu pohon Rp100.000. Jika ada mau pinjam Rp1 juta, harus punya 10 pohon jaminan.”
Dia mengatakan, kalau terumbu karang rusak atau dibom, atau pohon ditebang, kredit akan ditarik. Anggota kredit konservasi mempunyai tanggung jawab menjaga lingkungan.
“Lembaga adat berencana membeli tanah untuk lahan baru. Harapan ke depan, jadi lahan milik bersama untuk ditanami pohon baru.”
WWF Wakatobi membantu masyarakat sekitar mengadakan pertemuan rutin dan membuat AD/ART. Aturan main mengenai program sudah jelas.
Kamida, anggota kredit konservasi mengatakan, program ini sangat membantu nelayan dan petani di Wangi-wangi. Sebelum ada program, masyarakat banyak meminjam kepada tengkulak dengan bunga sangat tinggi.
“Saya dulu pinjam dana lewat kredit konservasi untuk modal dagang dengan jaminan mangga dan nangka.”
Anggota kredit konservasi kini berjumlah 20 orang. Di Pulau Wangwangi ada 12 kelompok nelayan dan petani rumput laut. Satu kelompok beranggotakan 20-30 orang. Perlahan, kesadaran mereka menjaga ekosistem mulai terlihat.
Setiap tanggal 6 mereka rutin bertemu. Tiap anggota harus membayar iuran Rp22.000. Dari jumlah itu Rp20.000 iuran wajib, Rp2.000 ribu konsumsi. Uang iuran dikumpulkan untuk keperluan simpan pinjam koperasi.
Anggota bisa meminjam dana untuk membeli bibit rumput laut, operasional perahu dan lain-lain. Sebagian dana untuk patroli laut dan pengembangan lembaga.
![Keramba Pulau Mas, yang hanya menjual ikan-ikan besar, bukan anakan. Foto: Indra Nugraha]()
Keramba Pulau Mas, yang hanya menjual ikan-ikan besar, bukan anakan. Foto: Indra Nugraha
![Patroli rutin yang dilakukan Balai TN Wakatobi. Meskipun begitu, karena keterbatasan anggaran dan personil mereka belum bisa mengawasi kawasan laut secara optimal. Beruntung, warga Wakatobi, bersama-sama menjaga kawasan laut dengan sukarela. Foto: Indra Nugraha]()
Patroli rutin yang dilakukan Balai TN Wakatobi. Meskipun begitu, karena keterbatasan anggaran dan personil mereka belum bisa mengawasi kawasan laut secara optimal. Beruntung, warga Wakatobi, bersama-sama menjaga kawasan laut dengan sukarela. Foto: Indra Nugraha
![Menimbang ikan di keramba Pulau Mas. Foto: Indra Nugraha]()
Menimbang ikan di keramba Pulau Mas. Foto: Indra Nugraha
Menilik Kepedulian Masyarakat Wakatobi dalam Menjaga Laut was first posted on August 14, 2014 at 11:56 am.