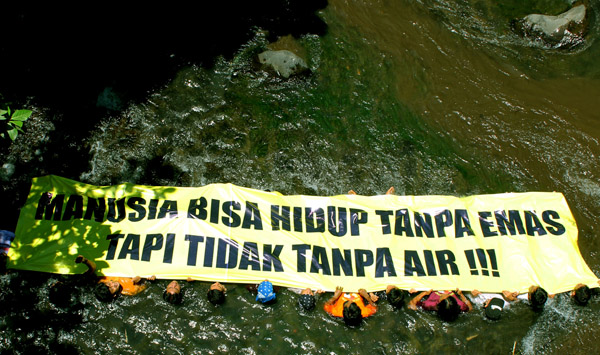![]()
Rumah warga adat yang dibakar dalam operasi gabungan TNBBS di Bengkulu. Konflik antara masyarakat adat dan taman nasional terus terjadi dan menyebabkan beberapa warga adat ditangkap. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang baru ini, semoga konflik-konflik masyarakat yang hidup di kawasan hutan baik dengan perusahaan maupun pemerintah bisa tertangani baik. Perspektif Kementerian LH dan Kehutanan pun bisa berubah dari logging timber based kepada ecosistem based (masyarakat adat bagian dari ekosistem karena sudah turun menurun tinggal di sana). Foto: AMAN Bengkulu
Siti Nurbaya Bakar, salah satu perempuan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat memperkuat kabinet kerja, yang baru saja, Minggu (26/10/14) diumumkan.
Siti, merupakan fungsionaris dari Partai Nasdem. Sebagai birokrat, terakhir masa jabatan sebagai sekretaris jenderal di Departemen Dalam Negeri pada 2005. Kini, dia juga ketua umum Himpunan Alumni Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di IPB.
Bagaimana tanggapan terhadap sosok menteri baru ini? Apa saja pekerjaan-pekerjaan yang mesti segera dijalankan? Berikut beberapa pandangan.
Martua Sirait, dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) mengatakan, Siti Nurbaya memiliki pengetahuan dan pengalaman mumpuni dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, katanya, dia pengajar lingkungan dan pemgembangan wilayah di pasca sarjana IPB. “Dia punya kemampuan me-main streaming perpektif lingkungan hidup ke dalam Kehutanan,” katanya kepada Mongabay, Minggu (26/10/14).
Meskipun begitu, katanya, kementerian ini kemungkinan menghadapi masalah besar mengintegrasikan perspektif lingkungan hidup dalam kerja-kerja nanti. Mengapa? Karena terkurung dalam pemahaman tentang kawasan hutan yang masih terjebak dalam teritori di luar atau di dalam kawasan hutan. Padahal, masalah lingkungan hidup melewati lingkup itu.
UU Kehutanan tahun 41 1999, ucap Martua, sebenarnya sudah meninggalkan perpektif lama kehutanan yaitu timber based kepada ecosistem based yang hampir sama dengan perpektif lingkungan hidup. “Namun, tidak mudah mengubah penjabaran dalam keseharian kerja, tanpa ada arahan jelas dari menteri-menteri sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa segera dijabarkan menteri yang baru.”
Menurut dia, ada beberapa pekerjaan urgen yang mesti mendapat perhatian segera. Pertama, pengkajian penerbitan izin-izin HTI diatas hutan gambut, konversi hutan gambut untuk kebun, pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang. “Ini semua tanpa kajian lingkungan hidup strategis. Ini contoh konkrit dari kesalahan paradigma pengurusan hutan,” ujar dia.
Kedua, pengalaman Siti Nurbaya sebagai sekjen Depdagri, meletakkan sentral untuk menyelesaikan status 30.000 desa beserta lahan lahan produktif di dalam kawasan hutan. Termasuk, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang kini terus mengalami kriminalisasi.
Ketiga, Siti Nurbaya sebagai ahli pengembangan wilayah, tentu paham proses tata ruang di daerah. Jadi, diharapkan bisa mendorong penjabaran kawasan perdesaan di dalam UU Tata Ruang 2007 baik di dalam dan di luar kawasan hutan.”
Sampai saat ini, katanya, mengenai kawasan pedesaan tidak pernah ada aturan turunan hingga ruang kelola masyarakat pedesaan habis dibagikan ke dalam izin-izin bagi usaha skala besar. “Saya rasa tiga hal mendasar ini harus dilakukan segera oleh Menteri LH dan Kehutanan yang baru guna menjawab buruknya tata kelola hutan dan lahan.”
Martua menyadari, dalam mewujudkan itu semua tidak dapat dijalankan sendiri oleh Menteri LH dan Kehutanan. Namun, perlu kerja koordinasi bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri. “Ini sejalan dengan peraturan bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, Mendagri dan Kepala BPN di KPK pada 17 Oktober 2014, beberapa hari sebelum habis masa jabatan Presiden SBY.”
Sementara Walhi menilai, penggabungan ini membuat situasi yang rumit bertambah rumit. Ketidakjelasan di publik tentang penjelasan atas nomenklatur kementrian ini menciptakan kekhawatiran.
![]()
Pulau Bangka di Sulut yang indah dan tempat tujuan wisatawan ini mulai merana. Tambang mulai masuk dan mulai mengancam keberadaan pulau cantik ini. Tambang percaya diri masuk, dengan mengantongi izin dari bupati, ternyata izin dari Kementerian ESDM. Dokumen lingkungan belum ada plus izin dari Kemenhut juga belum dipegang. Dengan, Kementerian LH dan Kehutanan, diharapkan pulau ini bisa selamat dari ancaman kehancuran. Foto: Save Bangka Island
Abetnego Tarigan, direktur eksekutif Walhi Nasional mengatakan, persoalan tata kelola hutan, salah satu dipengaruhi menumpuknya wewenang di Kemenhut selama ini. Asumsi, dengan ada wewenang besar dari hulu ke hilir akan memberikan dampak positif telah gagal di Kemenhut.
“Pengurusan hak atas tanah di kawasan hutan (tenurial), pemanfaatan hutan baik buat HTI, logging dan perhutanan sosial, konservasi dan pengawasan dan pengamanan kawasan hutan di Kemenhut selama ini gagal,” katanya.
Mengapa? Menurut dia, karena hutan lindung dikonversi tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, taman nasional rusak, kawasan HTI terbakar, konflik dengan masyarakat dan deforestasi berlanjut.
Penggabungan ini, ucap Abetnego, tidak memberikan indikasi ada distribusi kewenangan tetapi memperbesar kewenangan. “Asumsi lingkungan hidup akan menjadi arus utama sangat layak diragukan karena yang berpotensi terjadi arus utama kehutanan di lingkungan hidup. Akhirnya jebakan persoalan lingkungan hidup di Indonesia adalah persoalan kehutanan.”
Untuk itu, katanya agenda mendesak harus dikerjakan seperti 18 komitmen Jokowi yang disampaikan kala konferensi Walhi 14 Oktober 2014, yang dibacakan Anies Baswedan.
“Walhi akan menagih komitmen ini dalam pemerintahan kedepan. Proses pengawalan dan desakan akan terus dibangun guna memastikan Presiden memenuhi janji-janji itu.”
Tak hanya itu, katanya, ada beberapa hal lain yang mesti menjadi perhatian Presiden dan menteri. Pertama, jaminan tidak ada lagi masalah asap di tahun depan. Kedua, penyelesaian Peraturan Pemerintah di bawah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak dikerjakan pemerintahan SBY.
Ketiga, merehabilitasi kawasan-kawasan kritis di luar kawasan pesisir seperti kerusakan pada daerah-daerah aliran sungai utama seperti Citarum, dan Ciliwung. Keempat, membangun sistem peradilan lingkungan.Kelima, meninjau kembali kebijakan berisiko lingkungan hidup tinggi seperti MP3EI dan reklamasi pantai di berbagai wilayah.
Keenam, memastikan transformasi energi menuju energi ramah lingkungan. Ketujuh, penuntasan kasus-kasus hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Kedelapan, rasionalisasi dan perbaikan tata kelola bisnis di sektor sumber daya alam seperti HTI, pertambangan, perkebunan dan logging.
Kesembilan, jaminan perlindungan masyarakat atas dampak lingkungan sebagai akibat keputusan investasi dan pembangunan dan kesepuluh, pembuatan UU perubahan iklim.
Bagaimana menurut Abetnego sosok Siti Nurbaya? “Saya baru 12 tahun lebih berkecimpung di isu lingkungan dan sumber daya alam, saya belum pernah bersentuhan dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan ibu Siti Nurbaya,” ujar dia.
Dia menduga, ungkapan profesional yang dimaksud Presiden, kemungkinan lebih dominan pada aspek managerial. “Padahal umum dipahami, profesional itu aspek managerial dan kedalaman pemahaman atas kompleksitas isu yang ditangani.”
18 komitmen Jokowi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
1. Review terhadap perizinan yang diintegrasikan dalam satu peta (one map)2.Pelaksanaan penuh reforma agraria yang dimandatkan oleh tap MPR No. IX/20013.Penyelesaian konflik agraria yang selama ini terjadi4. Perbaikan tata ruang termasuk tata ruang pesisir
5. Pemulihan pencemaran dan perusakan hutan, terdiri dari penurunan kebakaran hutan dan lahan secara mendasar
6.Memulihkan 5,5 juta hektar kawasana sangat kritis bersama masyarakat
7.Pemulihan daerah aliran sungai yang kritis secara terintegrasi dengan melibatkan semua pihak
8.Membentuk Satgas anti mafia sumber daya alam yang bertanggung jawab langsung kepada saya
9.Pembentukan kanal aspirasi warga yang akan terus diawasi dan ditindaklanjuti
10. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana ekologis
11.Perlindungan total lahan terhadap hutan alam, lahan gambut serta daerah pesisir
12.Seluruh langkah yang akan kami dilakukan termasuk diplomasi internasional tentang perubahan iklim secara lebih efektif
13.Revolusi mental dalam mengelola lingkungan hidup juga merupakan sesuatu yang akan kami prioritaskan dalam bentuk beberapa langkah cepat secara maksimal dalam satu tahun pertama
14.Gerakan rakyat dalam pengelolaan sampah yang efektif melalui pendirian bank sampah di 5 sampai 10 kota besar sebagai projek utama dan pertama
15.Mencanangkan Januari 2015 tahun baru tanpa sampah
16. Percepatan implementasi tap MPR no IX/2001 tentang reforma agraria dan sumber daya alam
17. Memprioritaskan 7 kawasan pesisir yang akan juga merehabilitasi sabuk pantai
18. Berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan lingkungan hidup secara mendasar dalam pemerintahan yang akan datang
Sumber: Pidato tertulis Presiden Jokowi pada Konferensi Lingkungan Hidup Walhi di Jakarta 14 Oktober 2014 |
Kejelasan tugas dan wewenang
Tak jauh beda diungkapkan Longgena Ginting, kepala Greenpeace di Indonesia. Dia mengatakan, tugas pertama Kementerian LH dan Kehutanan tentu merestrukturisasi dua kelembagaan ini menjadi sebuah kementerian dengan tugas dan kewenangan yang jelas. “Publik pasti menanti keterangan lebih lanjut pertimbangan utama peleburan ini. Yang terpenting lagi apa mandat baru dari kementerian baru ini,” katanya.
Sebenarnya Longgena merasa khawatir dengan penggabungan LH dan Kemenhut ini. “Tetapi inilah real politics yang ada. Saya harap ada penjelasan soal ini dari pemerintah baru.”
Tugas-tugas mendesak lain segera dilakukan, katanya, adalah mengatasi perubahan iklim dengan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang kuat. “Indonesia, emiter karbon utama dunia dan sebagian besar dari kerusakan hutan dan kebakaran lahan gambut. Moratorium hutan perlu diteruskan dan komitmen penurunan emisi 26-41% perlu diperkuat.”
Menurut dia, mandat LH jauh lebih luas dari Kehutanan. Untuk itu, perlu ada kepastian bahwa masalah lingkungan lain seperti kelautan, energi, air, pencemaran udara bisa mendapat perhatian. “Ini pasti tantangan besar termasuk memastikan kewenangan LH justru tak menjadi marginal di dalam portofolio Kehutanan dan terjadi konflik kepentingan konservasi dan eksploitasi yang merugikan lingkungan.”
Deni Bram, pengajar Hukum Lingkungan Universitas Tarumanagara menilai, secara bahasa tutur Jokowi agak sulit mencari rasionalitas keberadaan Siti Nurbaya sebagai Menteri LH dan Kehutanan. “Berbeda saat Presiden memberikan penjelasan pada posisi menteri lain. Tanpa bermaksud mendahului, namun tugas besar menteri baru ini menanti ke depan,” katanya.
Menurut dia, dari peleburan dua kementerian ini, yang menjadi tantangan besar, yakni, perbaikan institusional mulai dari lembaga pusat hingga daerah. “Perlu diingat ketua MPR saat ini, (Zulkifli Hasan) mantan Menteri Kehutanan, sedikit banyak mempengaruhi kinerja Jokowi secara politis dalam menyeimbangkan dengan oposisi di parlemen,” ujar dia.
Untuk itu, fokus utama Siti Nurbaya, menurut Deni, adalah menjawab tantangan regulasi, menaikkan kelas Kementerian LH dan Kehutanan. “Ini jadi langkah awal yang bisa ditempuh.”
Secara nomenklatur, katanya, sudah satu kosong untuk LH yaitu menjadikan LH sebagai lead yang dapat dimaknai menjadi kiblat saat ini. Kehutanan akan tunduk pada rezim LH. Untuk itu, menteri bisa segera menuntaskan segala pekerjaan rumah, misal terkait pembuatan PP yang diamanatkan UU Lingkungan Hidup dan optimalkan struktur LH.
Dari daerah, Kussaritano, direktur eksekutif Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, menyatakan, menyingkronkan UU PPLH dan UU Kehutanan menjadi pekerjaan menteri baru agar tak makin banyak ketimpangan dan membuat masalah di daerah. “Tumpah tindih perizinan juga menjadi hal urgen buat diselesaikan,” ujar dia.
Menteri LH dan Kehutanan, katanya, mesti melakukan audit perizinan dan laksanakan amanat UU PPLH yang telah ‘menikah’ dengan UU Kehutanan.
![]()
Salah satu bagian hutan di Kalteng kondisi Maret 2014, yang terbabat buat perkebunan sawit. Perusakan hutan resmi ini boleh karena ada izin dari Kementerian Kehutanan. Aspek lingkungan seakan tak menjadi persoalan asal izin sudah dipegang. Dengan penggabungan dua kementerian ini, diharapkan aspek lingkungan hidup bisa menjadi perhatian serius dan penting sebelum memberi izin dengan alasan demi pembangunan. Foto: Lili Rambe
“Kawin” Kementerian LH dan Kehutanan, Kerja Berat Menanti Sang Menteri was first posted on October 26, 2014 at 11:26 pm.